AKTAMEDIA.COM, JAKARTA — Dalam era informasi yang dipenuhi klaim kebenaran instan, sebagaimana dilaporkan Viva.co.id tentang “Mengejutkan! Socrates Mengajarkan bahwa Ketidaktahuan Adalah Awal dari Kebijaksanaan Sejati”, Ditjen Aptika Kominfo, 23 Februari 2019 tentang “Era Post Truth Picu Penyebaran Berita Bohong”, dan penelitian ResearchGate, Desember 2024 mengenai “Disinformasi di Era Post-Truth: Ancaman terhadap Demokrasi dan Mobilitas Global”, dua tradisi filosofis klasik menawarkan pendekatan epistemologis (berkaitan dengan teori pengetahuan) yang paradoks (tampak bertentangan) namun mendalam: pengakuan terhadap ketidaktahuan sebagai fondasi kebijaksanaan sejati. Paradoks Socrates “saya tahu bahwa saya tidak tahu” dan konsep ‘syak manhaji’ (keraguan metodis/keraguan yang disengaja sebagai metode) Al-Ghazali menunjukkan konvergensi (pertemuan) pemikiran lintas peradaban tentang nilai epistemik (nilai pengetahuan) ketidaktahuan.
Kedua pemikir besar ini menghadapi tantangan serupa dalam konteks zaman masing-masing. Socrates berhadapan dengan para sofis (guru retorika yang mengklaim memiliki kebijaksanaan) yang mengklaim memiliki pengetahuan absolut tentang segala hal, sementara Al-Ghazali mengkritisi para filosof yang menyatakan superioritas pengetahuan demonstratif (pengetahuan yang dapat dibuktikan secara logis) mereka atas wahyu (Hadisi, 2021). Keduanya mengembangkan metode skeptis (meragukan) yang menggunakan ketidaktahuan bukan sebagai kekalahan intelektual, melainkan sebagai instrumen pencarian kebenaran yang lebih mendalam.
Paradoks Socrates, sebagaimana direkam Plato dalam “Apology,” menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari pengakuan jujur terhadap keterbatasan pengetahuan. Meskipun frasa “saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa” merupakan parafrasa dari pemikiran Socrates, konsep ini secara akurat mencerminkan filosofinya tentang methodological humility (kerendahan hati metodologis/sikap rendah hati dalam metode pencarian pengetahuan) yang membuka ruang untuk investigasi berkelanjutan (Burnyeat, 2012). Socrates mendemonstrasikan bahwa mereka yang mengklaim tahu segala sesuatu justru terperangkap dalam ilusi pengetahuan, sementara pengakuan terhadap ketidaktahuan menciptakan disposisi mental (kecenderungan berpikir) yang tepat untuk pembelajaran autentik (asli/sejati).
Dalam tradisi Islam, Al-Ghazali mengembangkan konsep ‘syak manhaji’ (keraguan metodis/keraguan yang disengaja sebagai metode pencarian kebenaran) dalam karyanya “Al-Munqidh min al-Dalal” (Penyelamat dari Kesesatan) sebagai respons terhadap krisis epistemologis (krisis pengetahuan) yang dialaminya. Mohamed (2024) menganalisis bagaimana Al-Ghazali menggunakan keraguan metodis bukan untuk mencapai skeptisisme radikal (keraguan total), tetapi untuk membangun fondasi epistemologis yang lebih solid (kuat). Berbeda dengan skeptisisme Pyrrhonian (aliran skeptis Yunani kuno) yang berujung pada suspense of judgment (penghentian penilaian) permanen, syak manhaji Al-Ghazali berfungsi sebagai mekanisme purifikasi kognitif (penyucian pemikiran) yang mempersiapkan pikiran untuk menerima pengetahuan yang lebih reliable (dapat diandalkan).
Meskipun keduanya menggunakan ketidaktahuan sebagai starting point epistemologis, terdapat perbedaan fundamental dalam telos atau tujuan akhir mereka. Socrates menggunakan pengakuan ketidaktahuan untuk memfasilitasi dialektika berkelanjutan dan pencarian kebenaran melalui elenchus, tanpa pretensi mencapai pengetahuan final (Burnyeat, 2017). Sebaliknya, Al-Ghazali menerapkan syak manhaji sebagai tahap transisional menuju certainty yang diperoleh melalui kashf (penyingkapan spiritual) dan pengalaman mistis yang memverifikasi kebenaran wahyu.
Analisis komparatif (perbandingan) menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini mengkritisi epistemological arrogance (kesombongan epistemologis/kesombongan dalam pengetahuan) dan intellectual complacency (kepuasan intelektual/rasa puas berlebihan terhadap pengetahuan). Socrates mengekspos ketidakkonsistenian dalam klaim pengetahuan para contemporaries (orang-orang sezaman)-nya melalui metode questioning (bertanya) yang sistematis. Al-Ghazali, dalam “Tahafut al-Falasifa” (Kerancuan Para Filosof), mendemonstrasikan bahwa argumen-argumen filosof yang diklaim demonstratif (dapat dibuktikan) sebenarnya bergantung pada premis-premis (proposisi dasar) yang tidak terbukti (Moad, 2007). Keduanya menggunakan skeptisisme sebagai alat kritik terhadap dogmatisme intelektual (sikap doktriner yang kaku), bukan sebagai posisi epistemologis final.
Relevansi kedua pendekatan ini dalam konteks kontemporer (masa kini) semakin signifikan di era post-truth (pasca-kebenaran/era dimana emosi lebih penting dari fakta) dan information overload (kebanjiran informasi). Pritchard (2012) menunjukkan bahwa prinsip epistemological humility (kerendahan hati epistemologis/sikap rendah hati dalam pengetahuan) yang diadvokasi Socrates dan Al-Ghazali dapat berfungsi sebagai antidote (penawar) terhadap cognitive bias (bias kognitif/kecenderungan berpikir yang menyimpang) dan confirmation bias (bias konfirmasi/kecenderungan mencari informasi yang mendukung keyakinan sendiri) yang merajalela dalam diskursus publik modern. Pengakuan terhadap ketidaktahuan mendorong intellectual honesty (kejujuran intelektual) dan openness (keterbukaan) terhadap evidence (bukti) baru.
Implementasi praktis (penerapan nyata) dari kedua metode ini memerlukan kultivasi (pengembangan) disposisi epistemik (kecenderungan pengetahuan) yang seimbang antara healthy skepticism (skeptisisme yang sehat) dan intellectual courage (keberanian intelektual). Seperti yang ditunjukkan Socrates, pengakuan ketidaktahuan tidak berarti intellectual paralysis (kelumpuhan intelektual), melainkan motivasi untuk investigasi (penyelidikan) yang lebih rigorous (ketat/teliti). Demikian pula, syak manhaji Al-Ghazali tidak berujung pada relativisme (paham yang menganggap kebenaran itu relatif), tetapi pada discriminating wisdom (kebijaksanaan yang membedakan) yang mampu membedakan antara klaim pengetahuan yang valid dan yang problematis (bermasalah).
Sintesis (penggabungan) dari kedua tradisi ini menawarkan framework epistemologis (kerangka kerja pengetahuan) yang valuable (berharga) untuk navigasi (mengarungi) kompleksitas intelektual kontemporer. Dengan mengintegrasikan Socratic questioning (metode bertanya ala Socrates) dengan rigorous doubt (keraguan yang ketat) ala Al-Ghazali, kita dapat mengembangkan epistemic virtues (kebajikan epistemik/keutamaan dalam pengetahuan) yang memungkinkan pursuit of knowledge (pencarian pengetahuan) yang lebih authentic (autentik/asli) dan humble (rendah hati). Dalam dunia yang sering dikuasai oleh false certainties (kepastian semu) dan intellectual arrogance (kesombongan intelektual), wisdom of ignorance (kebijaksanaan ketidaktahuan) yang diwariskan Socrates dan Al-Ghazali menjadi compass (kompas/penunjuk arah) yang invaluable (sangat berharga) untuk intellectual journey (perjalanan intelektual) yang genuine (asli/sejati).
Penulis adalah mahasiswa pascasarjana S3 Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau
Daftar Pustaka
Burnyeat, M. F. (2012). Explorations in ancient and modern philosophy (Vol. 1). Cambridge University Press.
Hadisi, R. (2021). Ghazālī’s transformative answer to scepticism. Theoria, 88(1), 109-142. https://doi.org/10.1111/theo.12282
Moad, E. O. (2007). Al-ghazali on power, causation, and ‘acquisition’. Philosophy East and West, 57(1), 1-13. https://doi.org/10.1353/pew.2007.0000
Mohamed, N. Y. (2024). Al-Ghazālī’s methodological skepticism and foundationalism. Journal of Islamic Philosophy, 15(1), 7-29.
Pritchard, D. (2012). Epistemological disjunctivism. Oxford University Press.
Vasalou, S. (2021). Al-Ghazālī and the idea of moral beauty. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003196556









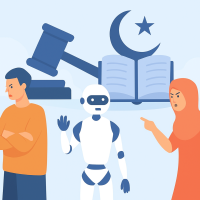

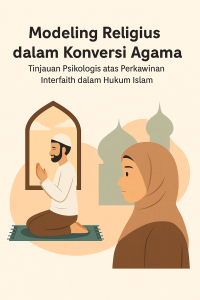




Leave a Reply