AKTAMEDIA.COM, JAKARTA — Fenomena perceraian akibat ketidakcocokan berkelanjutan atau syiqaq antara suami istri menghadirkan kompleksitas hukum yang memerlukan analisis mendalam terhadap harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Kasus perceraian Andre Taulany dan Erin Taulany yang diproses di Pengadilan Agama Tigaraksa (JPNN.com, 11 Agustus 2025) mengilustrasikan dilema klasik antara hak talak suami dengan keinginan istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
Syiqaq, yang secara etimologis berasal dari kata “syaqqo” yang bermakna membelah atau berpisah, dalam konteks hukum keluarga Islam merujuk pada perselisihan berkelanjutan antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara konvensional (Adegboyega, 2021). Kompilasi Hukum Islam (KHI atau himpunan aturan hukum Islam di Indonesia) Pasal 116 huruf (f) mengakomodasi konsep ini sebagai salah satu alasan perceraian, yakni “terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus”. Namun, implementasi konsep syiqaq dalam sistem peradilan Indonesia menghadapi tantangan interpretasi antara prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam perspektif fiqh (ilmu hukum Islam) klasik, syiqaq memiliki mekanisme penyelesaian khusus melalui institusi hakam (juru damai atau arbitrator) sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa (Surat Perempuan) ayat 35. Kedua hakam, yang mewakili keluarga suami dan istri, memiliki wewenang untuk memfasilitasi rekonsiliasi (perbaikan hubungan) atau memutuskan perceraian berdasarkan kondisi objektif rumah tangga (Kartini et al., 2022). Sebaliknya, hukum nasional Indonesia melalui Pengadilan Agama menerapkan pendekatan yang lebih struktural dengan menekankan mediasi (perantaraan) wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim tunggal atau majelis hakim. Perbedaan fundamental ini menciptakan dualisme prosedural yang berimplikasi pada efektivitas penyelesaian sengketa perkawinan (Ali et al., 2022).
Studi komparatif (perbandingan) menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia cenderung mengadopsi interpretasi syiqaq yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pemahaman fiqh tradisional. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa kriteria syiqaq tidak hanya terbatas pada konflik verbal atau fisik, tetapi diperluas mencakup ketidakharmonisan psikologis, perbedaan fundamental dalam orientasi hidup, dan ketidakmampuan mempertahankan komunikasi konstruktif (Hariati, 2021). Ekspansi interpretasi ini mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial kontemporer (masa kini), namun sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya parameter objektif yang universal untuk mengukur tingkat syiqaq.
Perbandingan dengan yurisdiksi (wilayah hukum) Muslim lainnya mengungkapkan variasi signifikan dalam penanganan syiqaq. Sistem peradilan keluarga di Malaysia dan Brunei Darussalam menerapkan pendekatan yang lebih konservatif dengan mensyaratkan bukti konkret tentang ketidakmungkinan rekonsiliasi sebelum mengabulkan perceraian berbasis syiqaq. Sementara itu, penelitian terhadap praktik khuluk (perceraian atas inisiatif istri) di Pakistan menunjukkan bahwa pengadilan telah mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam proses perceraian, termasuk memberikan hak inisiasi perceraian kepada istri dalam kasus syiqaq tanpa memerlukan persetujuan suami (Aman et al., 2021). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus (kesepakatan) universal dalam implementasi konsep syiqaq dalam hukum keluarga Muslim kontemporer.
Untuk mengatasi kompleksitas ini, diperlukan reformulasi konseptual yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan sistem hukum modern. Pertama, pengembangan kriteria objektif syiqaq melalui instrumen psikologis dan sosiologis yang dapat diaplikasikan secara konsisten oleh pengadilan. Kedua, penguatan institusi mediasi berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, peningkatan kapasitas hakim dan mediator melalui pelatihan khusus tentang dinamika psikologi keluarga dan metode penyelesaian sengketa alternatif. Keempat, pengembangan mekanisme tindak lanjut pasca-perceraian untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan istri sesuai dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam.
Konklusi (kesimpulan) penelitian ini menegaskan bahwa syiqaq sebagai alasan perceraian memerlukan pendekatan holistik (menyeluruh) yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga dimensi psikososial dan kultural dari konflik perkawinan. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani syiqaq harus dibangun atas fondasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai pilar fundamental masyarakat. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mengembangkan sistem hukum keluarga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dalam konteks modernitas.
Penulis adalah mahasiswa pascasarjana S3 Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau
Daftar Pustaka
Adegboyega, L. O. (2021). Influence of spousal communication on marital conflict resolution as expressed by married adults in Ilorin Metropolis, Kwara State: Implications for counseling practice. Canadian Journal of Family and Youth, 13(1), 71-83. https://doi.org/10.29173/cjfy29602
Ali, P. A., McGarry, J., & Maqsood, A. (2022). Spousal role expectations and marital conflict: Perspectives of men and women. Journal of Interpersonal Violence, 37(9-10), NP7082-NP7108. https://doi.org/10.1177/0886260520966667
Aman, J., Abbas, J., Lela, U., & Shi, G. (2021). Religious affiliation, daily spirituals, and private religious factors promote marital commitment among married couples: Does religiosity help people amid the COVID-19 crisis? Frontiers in Psychology, 12, 657400. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.657400
Hariati. (2021). Livelihood issues as a cause of divorce in the perspective of Islamic family law. Syiah Kuala Law Journal, 5(1), 79-95.
Kartini, K., Samin, S., Talli, A. H., Kurniati, K., & Bakri, M. (2022). Maqasid Al-Shari’ah perspectives in solution of divorce cases for early marriage. International Journal of Health Sciences, 6(S5), 8685-8697. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.11775









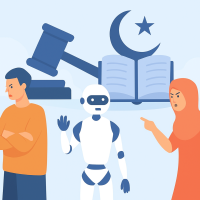

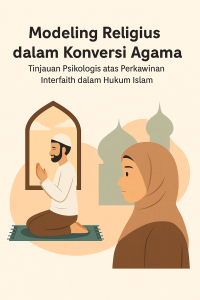




Leave a Reply