AKTAMEDIA.COM, JAKARTA — Fenomena perceraian yang dipicu oleh perubahan status sosial-ekonomi salah satu pasangan semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Sebagaimana dilaporkan Harian Fajar, 27 Juli 2025, kasus viral seorang istri yang menceraikan suaminya setelah diangkat menjadi PNS karena merasa malu memiliki suami kuli bangunan, serta 50 kasus serupa di Pandeglang yang melibatkan guru PPPK, menunjukkan urgensi pemahaman kembali konsep kafa’ah (kesetaraan/kesepadanan dalam pernikahan) dalam pernikahan Islam sebagai fondasi stabilitas rumah tangga.
Disparitas (ketimpangan) status sosial-ekonomi dalam pernikahan bukanlah fenomena baru, namun kasus-kasus seperti yang terjadi di Pandeglang menunjukkan intensitas masalah yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena guru yang mengajukan gugatan cerai setelah diangkat sebagai PPPK mencerminkan pergeseran orientasi pernikahan dari nilai-nilai spiritual menuju materialisme. Dalam konteks hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan rahmat). Fenomena ini menuntut revitalisasi (pembaruan) pemahaman konsep kafa’ah sebagai prinsip fundamental dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang tidak mudah goyah oleh perubahan status sosial-ekonomi.
Konsep kafa’ah dalam literatur fiqh (ilmu hukum Islam) klasik didefinisikan sebagai kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut para ulama, kafa’ah mencakup enam dimensi utama: agama (din – ketakwaan), keturunan (nasab – garis keturunan), profesi (hirfah – pekerjaan), kekayaan (mal – harta), kebebasan (hurriyyah – status kemerdekaan), dan akhlak (khuluq – budi pekerti) (Nurlaelawati, 2020). Imam Syafi’i menekankan bahwa aspek agama merupakan prioritas utama dalam kafa’ah, sementara Imam Abu Hanifah memberikan fleksibilitas lebih besar pada aspek sosial-ekonomi. Keempat mazhab (aliran hukuk Islam) Sunni secara konsisten sepakat bahwa kompatibilitas (keserasian) agama dan akhlak merupakan fondasi paling fundamental, sementara aspek material bersifat sekunder dan dapat berubah seiring waktu.
Realitas kasus-kasus seperti yang dilaporkan media menunjukkan adanya distorsi (penyimpangan) dalam pemahaman kafa’ah di masyarakat kontemporer. Penelitian Sulaiman dan Wibowo (2023) mengungkapkan bahwa sistem pernikahan yang terlalu menekankan kesetaraan status sosial sering mengabaikan nilai fundamental kemanusiaan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kasus istri yang menceraikan suami kuli bangunan setelah menjadi PNS menunjukkan pemahaman kafa’ah yang terbalik—mengorbankan loyalitas dan komitmen demi prestise sosial. Padahal, dalam kafa’ah yang sesungguhnya, perubahan status ekonomi seharusnya memperkuat ikatan pernikahan melalui rasa syukur dan solidaritas, bukan merusaknya melalui arogansi dan rasa malu.
Analisis terhadap fenomena Pandeglang dan kasus serupa menunjukkan paradoks (kontradiksi) dalam implementasi (penerapan) nilai-nilai Islam modern. Di satu sisi, mobilitas sosial melalui pendidikan dan karier merupakan anjuran Islam yang mendorong umat untuk terus memperbaiki kondisi hidup. Namun di sisi lain, ketika pencapaian tersebut justru merusak komitmen pernikahan, hal ini bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang menjaga institusi keluarga. Jones (2023) dalam penelitiannya tentang tren perceraian Muslim di Asia Tenggara menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial-ekonomi memang berpengaruh terhadap stabilitas pernikahan, namun yang terpenting adalah bagaimana pasangan mengelola perubahan tersebut dalam kerangka nilai-nilai spiritual yang kuat.
Solusi komprehensif (menyeluruh) terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan edukasi syariah, konseling (bimbingan konsultasi) pernikahan, dan penguatan pemahaman fiqh munakahat (ilmu hukum pernikahan Islam). Pertama, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat kurikulum fiqh munakahat yang menekankan kafa’ah sebagai kompatibilitas dinamis, bukan kesetaraan statis. Kedua, program bimbingan pra-nikah harus memasukkan simulasi pengelolaan perubahan status sosial-ekonomi dalam rumah tangga. Ketiga, konselor pernikahan Muslim perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang kafa’ah kontekstual (sesuai konteks) yang dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan modern. Keempat, tokoh agama dan da’i perlu aktif mengkampanyekan pemahaman kafa’ah yang holistik (menyeluruh) melalui khutbah, ceramah, dan media sosial.
Fenomena perceraian akibat disparitas status sosial-ekonomi seperti yang terjadi di Pandeglang menunjukkan urgensi pemahaman autentik terhadap konsep kafa’ah dalam pernikahan Islam. Kafa’ah sejati bukan terletak pada kesetaraan material yang kaku, melainkan pada kompatibilitas spiritual-moral yang mampu menghormati dan mensyukuri perubahan kehidupan bersama. Masyarakat Muslim Indonesia perlu kembali merenungi esensi pernikahan sebagai ikatan sakral yang dibangun atas fondasi ketakwaan, kesetiaan, dan komitmen untuk saling menguatkan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kasus-kasus perceraian yang dipicu oleh prestise sosial harus menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa kesuksesan duniawi yang tidak diimbangi dengan penguatan spiritual justru dapat menghancurkan institusi pernikahan yang telah dibangun dengan susah payah.
Penulis adalah mahasiswa pascasarjana S3 prodi Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau
Daftar Pustaka
Jones, G. W. (2023). Muslim and non-Muslim divorce trends in Southeast Asia in the 21st century. Demographic Research, 49(15), 419-454. https://doi.org/10.4054/DemRes.2023.49.15
Nurlaelawati, E. (2020). Maqashid al-syari’ah concept of kafa’ah in marriage. An-Nur: Jurnal Studi Islam, 20(1), 107-116. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651
Sulaiman, A., & Wibowo, H. (2023). Equality (kafa’ah) in marriage: A dialogue of Islamic, state, and customary law in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 11(8), e1495.




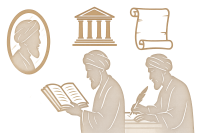

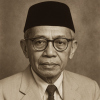










Leave a Reply