AKTAMEDIA.COM, JAKARTA — Pemikiran Muhammad Natsir tentang Ibnu Sina merepresentasikan sintesis brilian antara tradisi rasionalisme Islam klasik dengan kebutuhan epistemologis Islam modern, di mana integrasi antara wahyu dan akal menjadi fondasi metodologis yang relevan bagi perkembangan intelektual Muslim kontemporer.
https://fliphtml5.com/vkixl/rjcc/Capita_Selecta_Jilid_1/
Dalam konteks sejarah intelektual Islam Indonesia, Muhammad Natsir menghadapi tantangan kompleks untuk mengartikulasikan posisi Islam yang dapat mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan autentisitas spiritual. Tulisan Natsir tentang Ibnu Sina menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap warisan filosofis Islam yang dapat menjembatani kesenjangan (gap) antara tradisi dan modernitas. Sebagaimana ditekankan dalam penelitian Latief & Nashir (2020), gerakan modernis Islam Indonesia telah menunjukkan keterlibatan yang dinamis (engagement yang vibrant) dalam aktivisme religius dan sosial yang melampaui konteks domestik Indonesia, mencari keseimbangan antara pelestarian (preservasi) nilai-nilai autentik dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
Argumen utama Natsir terletak pada rekonseptualisasi (perumusan ulang) hubungan antara wahyu (al-wahy) dan akal (al-‘aql) dalam kerangka epistemologi (teori pengetahuan) Islam. Mengacu pada pemikiran Ibnu Sina yang menggabungkan berbagai untaian pemikiran filosofis/ilmiah dalam antiquitas (zaman kuno) Yunani akhir dan Islam awal menjadi sistem ilmiah yang rasional dan konsisten secara mandiri, Natsir mengembangkan tesis bahwa akal manusia bukan merupakan instrumen yang bertentangan dengan wahyu, melainkan alat yang dianugerahkan Allah untuk memahami dan mengaktualisasikan petunjuk-Nya. Kemampuan Avicenna (nama Latin untuk Ibnu Sina) untuk mensintesis (memadukan) dan memperluas berbagai tren intelektual zamannya, termasuk tradisi Yunani dan tradisi teologis Islam (Kalām atau ilmu kalam), menjadi inspirasi bagi Natsir dalam merumuskan metodologi integratif (penggabungan).
Dimensi kedua dari analisis Natsir mencakup kritik konstruktif terhadap dikotomi (pemisahan yang tajam) antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah mengakar dalam sistem pendidikan Islam. Melalui pembacaan terhadap karya Ibnu Sina, Natsir mendemonstrasikan bahwa Ibn Sina sebagai seorang Muslim yang taat berusaha mendamaikan filosofi rasional dengan teologi (ilmu ketuhanan) Islam, bertujuan membuktikan keberadaan Allah dan penciptaan dunia secara ilmiah melalui akal dan logika. Perspektif ini menunjukkan bahwa integrasi holistik (menyeluruh) antara berbagai disiplin ilmu bukan hanya mungkin, tetapi merupakan keharusan dalam tradisi intelektual Islam yang autentik (asli).
Analisis komparatif (perbandingan) menunjukkan bahwa pemikiran Natsir tentang Ibnu Sina memiliki keunggulan metodologis dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain dalam wacana intelektual Islam Indonesia. Berbeda dengan kalangan tradisionalis yang cenderung kaku (rigid) dalam interpretasi teks, atau kalangan sekularis yang mengabaikan dimensi spiritual, Natsir menawarkan paradigma (kerangka pemikiran) “rasionalisme transendental” yang mengakui otoritas wahyu sambil memberdayakan kapasitas rasional manusia secara optimal. Sebagai salah satu tokoh politik dan pemikir terkemuka sejak periode kolonial di Indonesia, Natsir sebagai nasionalis Indonesia dan aktivis politik-religius telah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip integrasi ini dalam berbagai aspek kehidupan.
Implikasi praktis dari pemikiran Natsir mencakup reformulasi (perumusan kembali) sistem pendidikan Islam yang dapat menghasilkan generasi Muslim yang secara simultan menguasai sains modern dan memiliki kedalaman spiritual. Konseptualisasi (perumusan konsep) Natsir tentang “akal yang beriman” (believing reason) dapat dioperasionalisasikan melalui pengembangan kurikulum terintegrasi yang menempatkan Al-Qur’an sebagai pandangan dunia (worldview) sekaligus mengapresiasi kontribusi sains dan filsafat dalam mengungkap keagungan ciptaan Allah. Model pemikiran Avicenna yang menunjukkan bahwa dunia dapat sekaligus eternal (kekal) dan diciptakan, secara kontinyu dibawa ke dalam eksistensi, memberikan kerangka teoretis untuk memahami relasi antara sains dan agama.
Relevansi kontemporer pemikiran Natsir tentang Ibnu Sina semakin signifikan dalam menghadapi tantangan epistemologis (berkaitan dengan teori pengetahuan) era digital dan globalisasi. Kemampuan umat Islam untuk berkontribusi dalam perkembangan peradaban manusia sangat tergantung pada kapasitas mereka untuk mengintegrasikan kebijaksanaan tradisional (wisdom tradisional) dengan inovasi kontemporer. Pemikiran Natsir menawarkan kerangka kerja teoretis (framework teoretis) yang memungkinkan Muslim untuk menjadi agen transformasi peradaban tanpa kehilangan identitas spiritual, suatu urgensi yang semakin krusial dalam dinamika geopolitik dan intelektual global saat ini.
Penulis adalah mahasiswa pascasarjana S3 prodi Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau
Daftar Pustaka
Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local dynamics and global engagements of the Islamic modernist movement in contemporary Indonesia: The case of Muhammadiyah (2000-2020). Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(2), 188-209. https://doi.org/10.1177/1868103420910514
McGinnis, J. (2022). Ibn Sina’s natural philosophy. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2024 Edition). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/ibn-sina-natural/
Rahman, F. (2023). Muhammad Natsir: Sumbangannya terhadap perjuangan agama dan bangsa di Indonesia. Journal of Al-Tamaddun, 18(1), 45-62. https://doi.org/10.22452/jat.vol18no1.4
Wisnovsky, R. (2021). Ibn Sina (Avicenna). In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/ibn-sina/
Zulkarnain, A., & Hidayat, M. (2023). Nationalism thoughts of Ahmad Hassan, M. Isa Anshary, and M. Natsir: A study of the works of Islamic thinkers in the city of Bandung, Indonesia. Cogent Arts & Humanities, 10(1), 2281049. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2281049









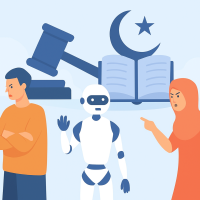

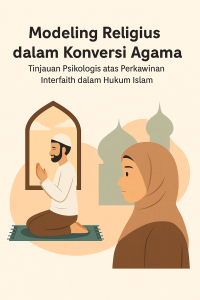




Leave a Reply