Fenomena konversi agama dalam konteks perkawinan interfaith (lintas agama) menunjukkan kompleksitas psikologis dan spiritual yang mendalam. Dalam masyarakat Muslim, konversi sering kali menjadi syarat legal dan religius untuk melangsungkan perkawinan, menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi pasangan non-Muslim. Salah satu strategi yang muncul dalam proses ini adalah modeling religius (peneladanan keagamaan)—yakni penampilan praktik keagamaan oleh pasangan Muslim sebagai bentuk persuasi spiritual.
Konversi religius bukan sekadar perubahan identitas formal, melainkan proses psikologis yang melibatkan krisis eksistensial, pencarian makna, dan interaksi sosial yang intens. Snook, Williams, dan Horgan (2019) menekankan bahwa konversi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti integrasi sosial, emosi, dan identitas, serta peran signifikan dari figur religius dalam kehidupan individu. Dalam konteks perkawinan, pasangan sering menjadi significant other (figur penting secara emosional) yang memicu reevaluasi sistem kepercayaan melalui interaksi spiritual yang mendalam.
Konsep modeling religius (peneladanan keagamaan) berakar pada social learning theory (teori pembelajaran sosial) dari Bandura, yang menyatakan bahwa individu dapat mengadopsi perilaku melalui observasi terhadap model yang relevan. Ketika pasangan non-Muslim menyaksikan praktik ibadah yang dilakukan dengan khusyuk dan konsisten, terjadi proses vicarious learning (pembelajaran melalui pengamatan) yang dapat memicu rasa ingin tahu spiritual dan refleksi terhadap keyakinan pribadi. Meskipun belum banyak studi empiris yang secara langsung menguji aktivasi mirror neurons (neuron cermin) dalam konteks ritual religius, pendekatan ini sejalan dengan teori neuropsikologis tentang resonansi emosional dalam interaksi sosial.
Namun, tidak semua konversi mencerminkan transformasi spiritual yang autentik. Van Niekerk dan Verkuyten (2018) menunjukkan bahwa sikap terhadap perkawinan interfaith (lintas agama) di negara mayoritas Muslim cenderung negatif, terutama terhadap perempuan, dan dipengaruhi oleh kekuatan keyakinan religius. Hal ini dapat mendorong konversi yang bersifat instrumental (berorientasi tujuan praktis)—dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif atau tekanan relasional. Konversi semacam ini berisiko menghasilkan religious commitment (komitmen religius) yang dangkal dan konflik identitas jangka panjang.
Untuk menghindari konversi yang bersifat superficial (dangkal), diperlukan pendekatan holistik (menyeluruh) yang mengintegrasikan aspek psikologis, teologis, dan legal. Rekomendasi praktis meliputi:
- Premarital counseling (konseling pra-nikah) yang membahas ekspektasi spiritual secara terbuka.
- Theological education (edukasi teologis) yang sistematis dan inklusif.
- Penciptaan safe space (ruang aman) untuk eksplorasi spiritual tanpa tekanan.
- Waktu refleksi yang cukup sebelum keputusan konversi.
- Dukungan post-conversion (pasca-konversi) untuk integrasi identitas religius yang sehat.
Institusi keagamaan dan legal perlu mengembangkan protokol yang lebih sensitif terhadap dinamika psikologis dan spiritual pasangan interfaith (lintas agama), memastikan bahwa konversi bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan hasil dari pencarian makna yang genuine (tulus dan otentik).
Daftar Pustaka
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.
Snook, D. W., Williams, M. J., & Horgan, J. G. (2019). Issues in the sociology and psychology of religious conversion. Pastoral Psychology, 68(3), 223–240.
Van Niekerk, J., & Verkuyten, M. (2018). Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach. International Journal for the Psychology of Religion, 28(4), 257–270.


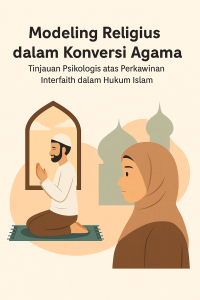














Leave a Reply